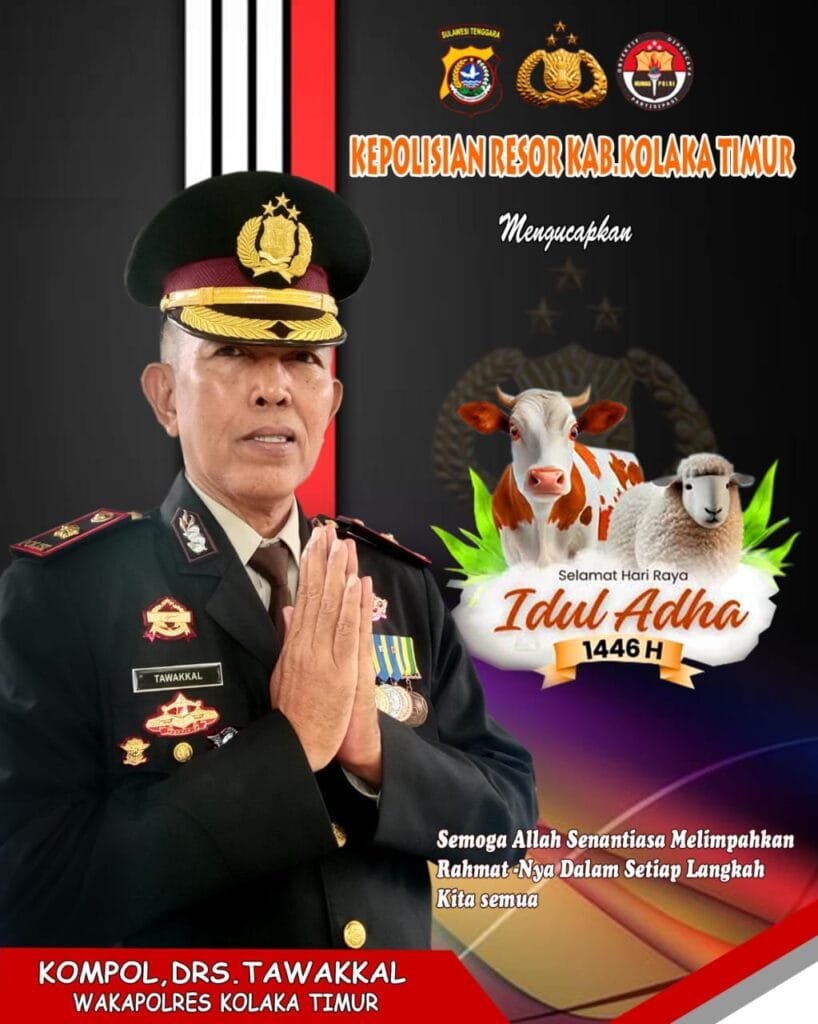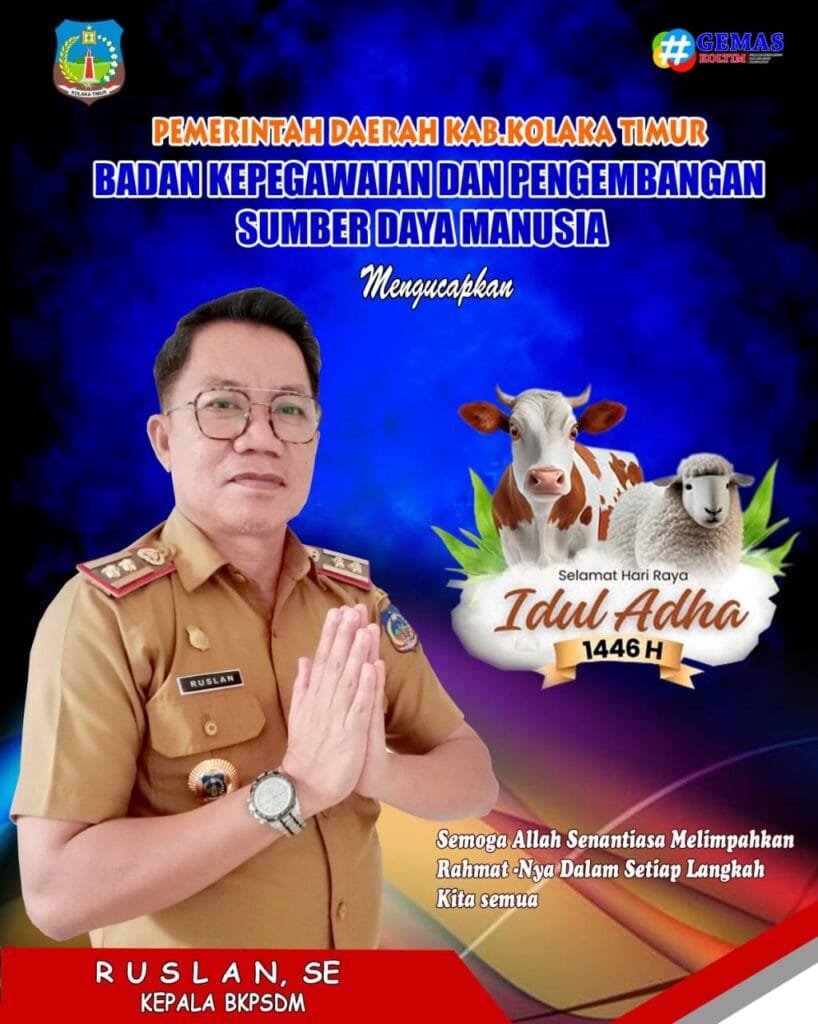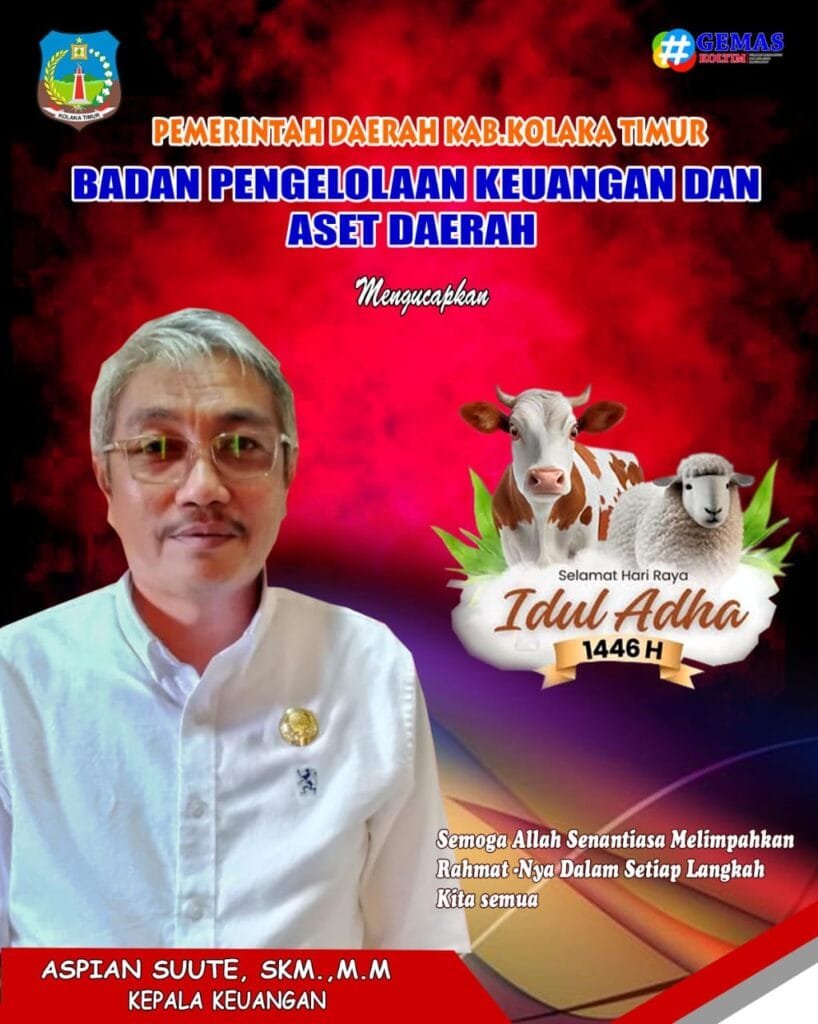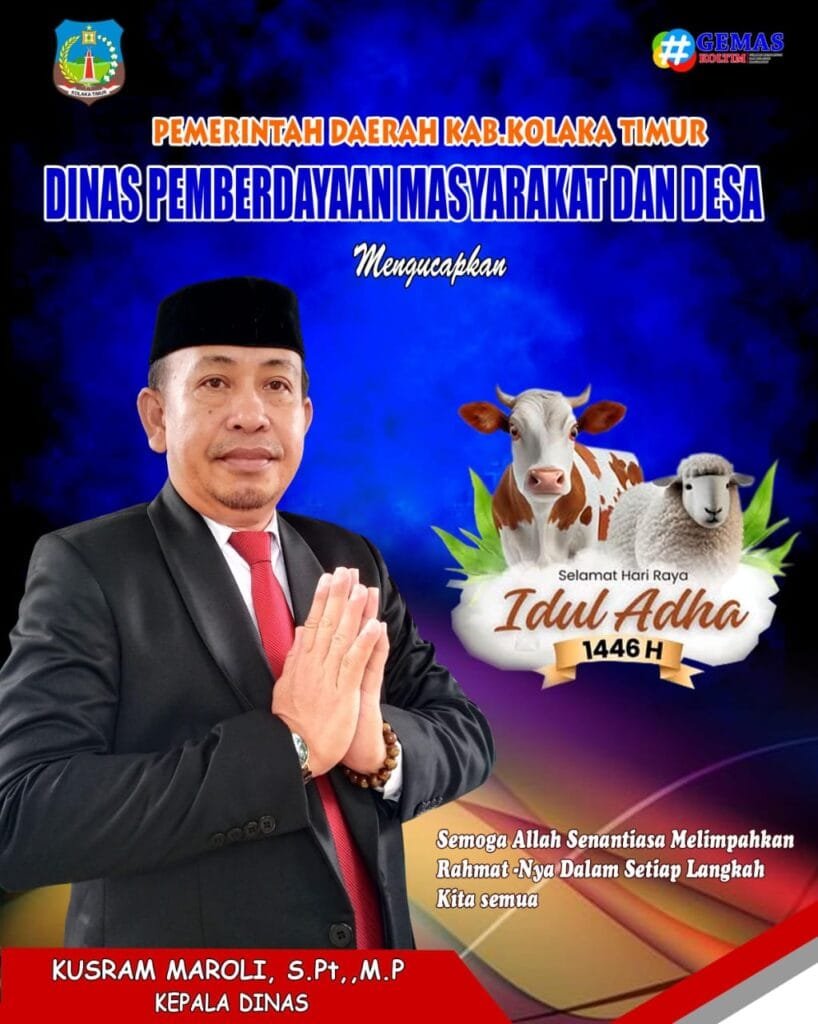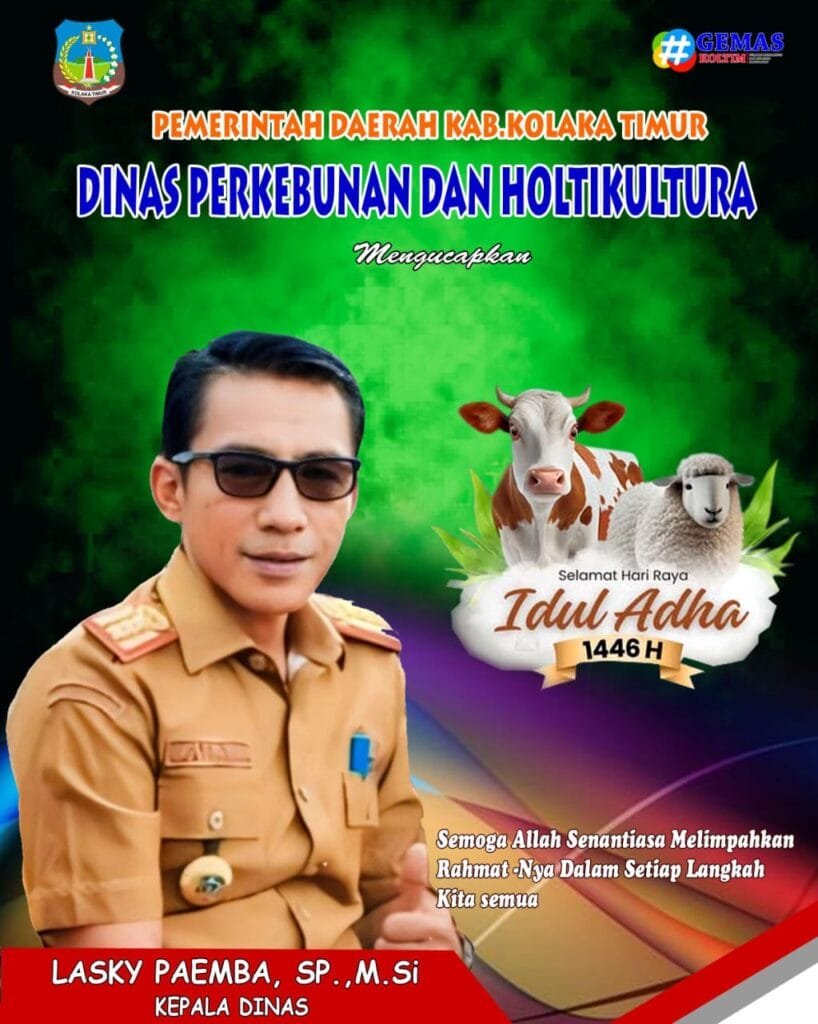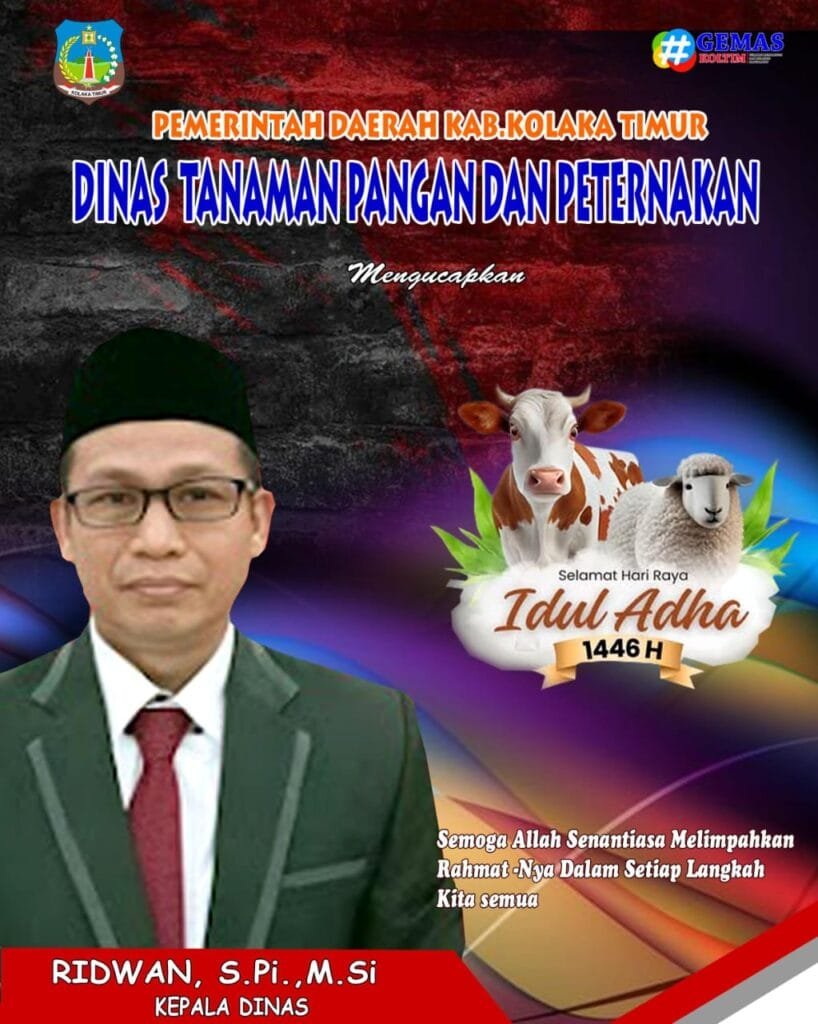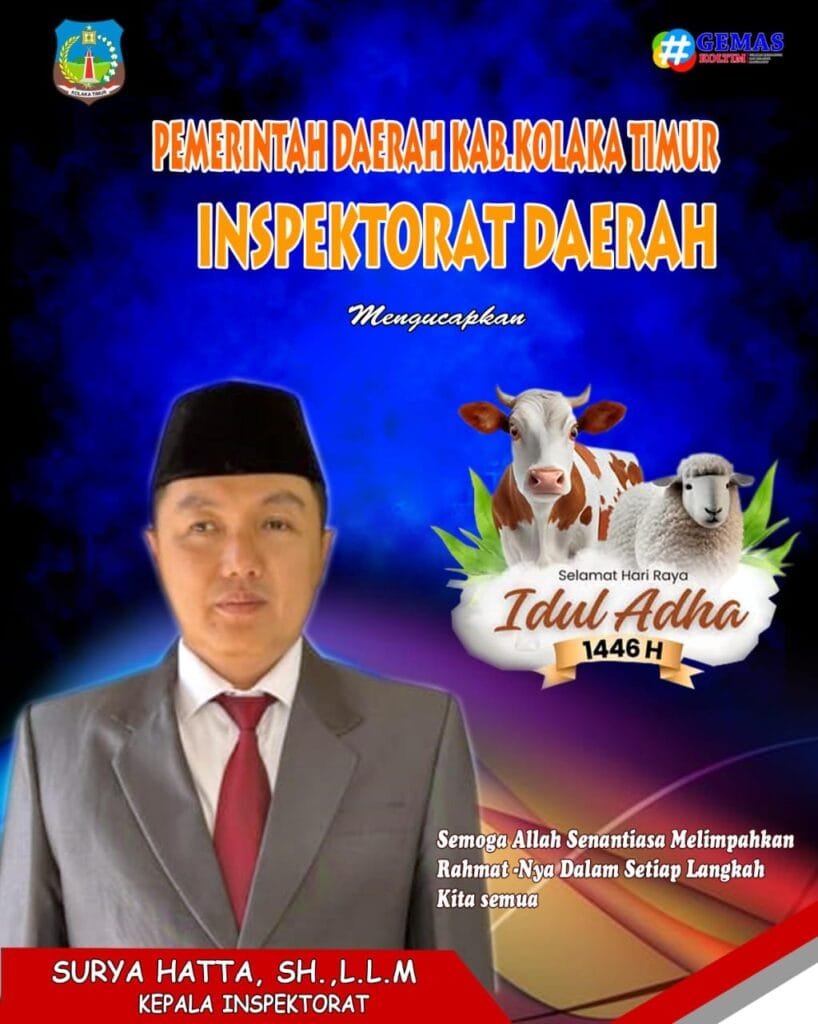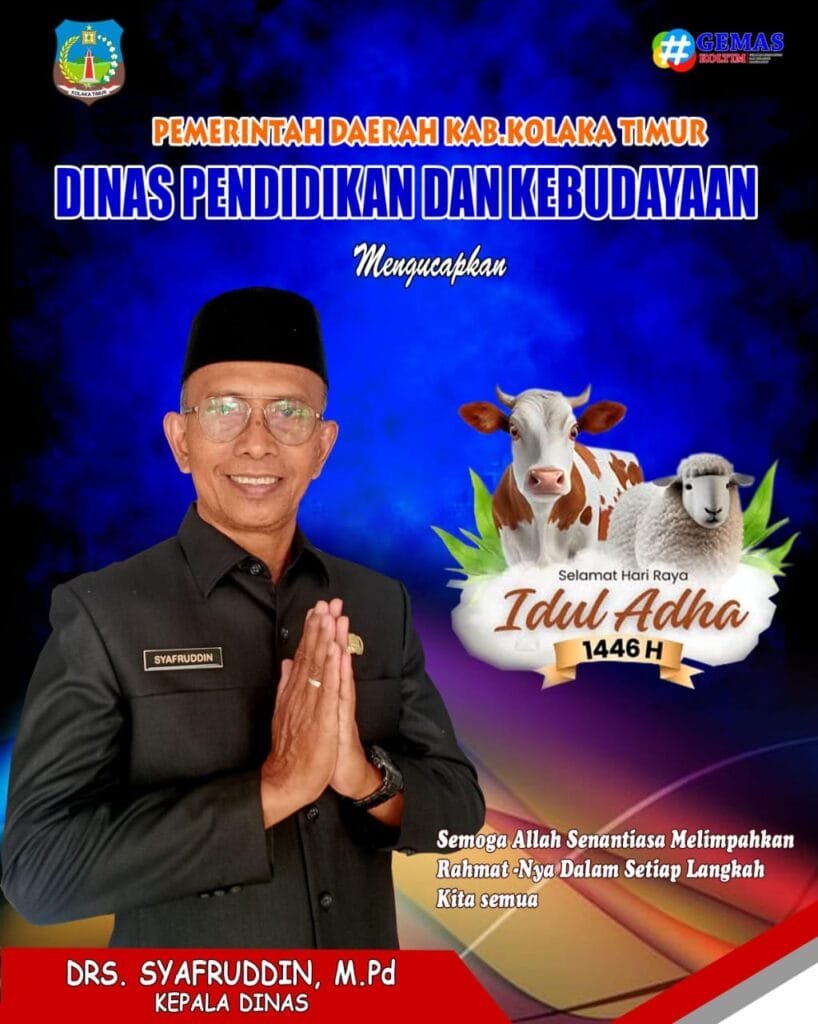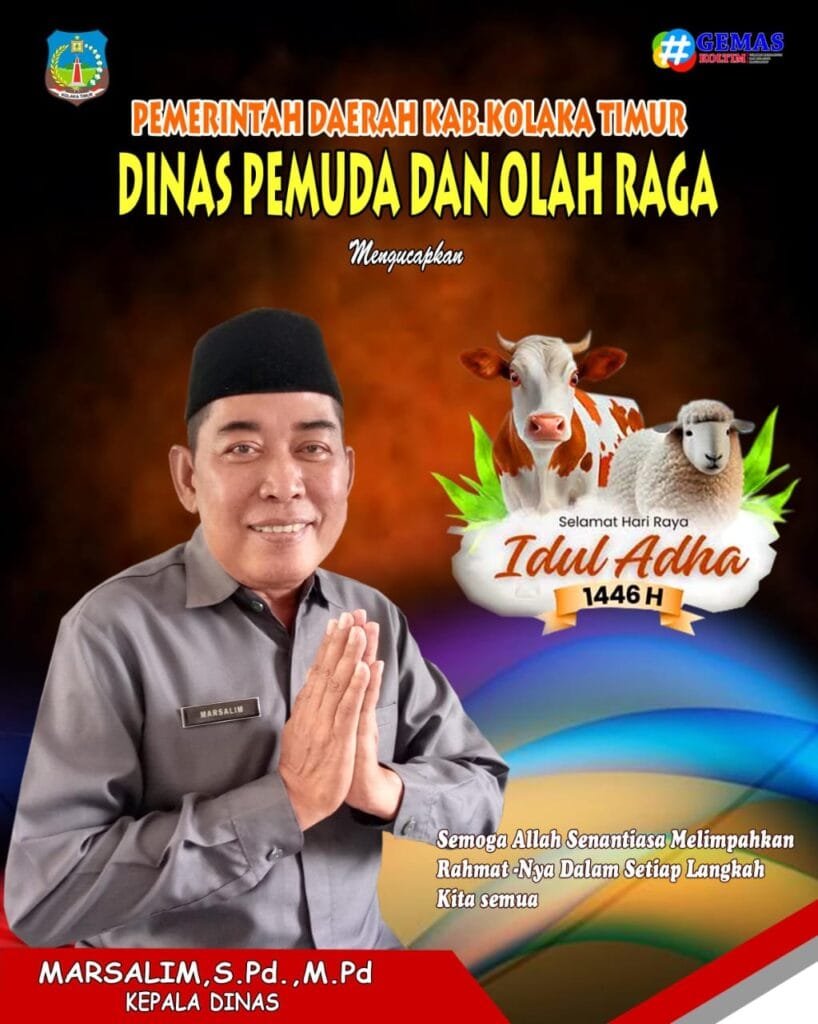Pendahuluan : Antara Label “Tertinggal” dan Kenyataan Kompleks, dengan pendekatan multidisipliner.
nuansasultra.com – Label “tertinggal” kerap disematkan pada suku Moronene tanpa pemahaman yang utuh terhadap sejarah dan konteksnya. Padahal, perjalanan panjang peradaban dari salah satu suku tertua di Sulawesi Tenggara ini menyimpan banyak simpul yang tak terbaca serta narasi yang luput dari sorotan sejarah resmi.
Apakah benar Moronene tertinggal karena faktor keturunan? Ataukah keterbelakangan itu merupakan hasil dari jalur sejarah yang berliku, geografi yang meminggirkan, dan dinamika internal yang belum sepenuhnya berdamai? Atau mungkin, stigma tersebut lahir dari akumulasi problem sosial, ekonomi, dan politik yang tak terselesaikan? Ataukah masyarakatnya memang belum memiliki daya juang kolektif yang cukup kuat untuk mengubah nasib mereka?
Tulisan ini berupaya menelusuri lebih jauh akar keterpinggiran tersebut melalui lensa sejarah, geografi, antropologi, hingga psikologi kolektif—agar kita tidak hanya mengeluh, tetapi mulai mengerti, merefleksikan, dan menyusun kembali langkah menuju masa depan.
Jejak Sejarah yang Terlupakan : Dari Migrasi ke Marjinalisasi.
Suku Moronene merupakan kelompok penutur awal bahasa Austronesia yang bermigrasi dari kawasan Yunnan (Tiongkok bagian Selatan), melalui Filipina dan Sulawesi Utara, sebelum akhirnya menetap di jazirah tenggara Pulau Sulawesi. Sebagai penghuni awal, mereka pernah mendiami wilayah luas dari Kolaka Utara, Kendari, hingga Bombana. Namun seiring waktu, arus migrasi suku Tolaki dan kehadiran suku-suku lainnya mendorong komunitas Moronene semakin ke wilayah paling tenggara.
Pada masa-masa awal itu, komunitas Moronene mulai membentuk koloni baru. Dari kelompok-kelompok kecil yang hidup dalam klan, mereka berkembang menjadi tobu-tobu (perkampungan tradisional) yang kemudian melahirkan sistem kepemimpinan lokal (chieftain) berbasis adat.
Ketika kerajaan besar seperti Gowa, Luwu, Bone, dan Buton mulai berkembang dan mengonsolidasikan kekuasaan di kawasan timur Nusantara, Kerajaan Moronene justru terbentuk lebih belakangan dan kerap menjadi vassal atau entitas subordinat dalam struktur politik regional. Di masa kolonial, Moronene menjadi bagian dari distrik di bawah Kesultanan Buton, sempat berdiri sendiri selama pendudukan Jepang, dan kembali berada di bawah pemerintahan Swapraja Buton setelah Indonesia merdeka.
Alih-alih menjadi pelaku utama sejarah, suku Moronene lebih sering tampil sebagai penonton atau bahkan korban. Pada masa pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), wilayah mereka turut mengalami kekerasan dan gangguan keamanan yang meninggalkan trauma kolektif. Narasi besar bangsa pun nyaris tak pernah menyebut mereka. Di sanalah marginalisasi dimulai—bukan karena kekalahan perang, tetapi karena hilangnya nama dalam catatan sejarah.
Dan ketika wilayah Moronene hendak dimekarkan dari Kabupaten Buton, nama “Moronene” bahkan mendapatkan penolakan. Nama kompromi “Kabupaten Bombana” akhirnya dipilih sebagai jalan tengah.
Warisan Lokal yang Diabaikan : Antara Pengetahuan Tradisional dan Ketidakpercayaan Diri Kolektif.
Suku Moronene sejatinya bukan kelompok tanpa modal peradaban. Dari arsitektur rumah yang adaptif terhadap iklim, hingga pengetahuan bintang (astronomi lokal) dan etnobotani yang kompleks, mereka pernah menjalani hidup selaras dengan alam dan musim. Namun, seiring perubahan zaman, banyak dari kearifan ini terkubur bersama para tetua, tidak pernah terdokumentasi secara sistematis.
Lemahnya tradisi literasi, tidak adanya aksara, serta ketergantungan pada oral tradition—meski kuat dalam cerita dan makna—menjadi titik rawan dalam mempertahankan jejak pengetahuan. Dalam banyak kasus, budaya Moronene lebih sering diposisikan sebagai ‘warisan museum’ ketimbang inspirasi masa depan.
Lebih menyedihkan lagi, terdapat kecenderungan psikologis yang menginternalisasi keterpinggiran: semacam inferiority complex kolektif. Ini membuat generasi muda enggan tampil membawa identitas Moronene. Keterbelakangan bukan hanya karena faktor eksternal, tapi juga karena kita enggan percaya bahwa warisan kita layak dibanggakan.
“Kadang yang menghalangi kemajuan bukan minimnya potensi, tapi keyakinan bahwa kita layak maju.”
Ketika Peta Sejarah Tak Berpihak : Di Mana Kesempatan Terlewat?
Buku Guns, Germs, and Steel karya Jared Diamond menjadi referensi penting dalam memahami mengapa sebagian bangsa di dunia tumbuh lebih unggul dibanding yang lain. Dalam kerangka berpikir J. Diamond, faktor geografi dan lingkungan memainkan peran besar dalam membentuk keunggulan peradaban. Wilayah Moronene, meskipun dianugerahi tanah yang subur dan kaya sumber daya alam, pada masa lampau tidak berada di jalur perdagangan utama seperti Buton, Kendari, atau Makassar. Tidak ada pelabuhan besar, tidak ada pusat niaga yang tumbuh pesat hal ini menjelaskan sebagian kondisi keterisolasian wilayah Moronene secara struktural.
Sekitar tahun 1613, ketika utusan VOC pertama kali menginjakkan kaki di tanah Moronene, mereka mencatat keberadaan 14 tobu (perkampungan). Namun, ketertarikan mereka tidak berlanjut. Wilayah ini dianggap terlalu terpencil, tanpa akses memadai untuk mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi barang.
Di sisi lain, perspektif The Geography of Genius karya Eric Weiner memberikan pendekatan yang lebih sosial-kultural. Weiner berargumen bahwa kejeniusan suatu bangsa tidak ditentukan oleh ras atau genetika, tetapi oleh kombinasi rasa ingin tahu, keteraturan sosial, dan dinamika kreativitas yang memantik inovasi. Dalam konteks ini, masyarakat Moronene cenderung terjebak dalam stagnansi sosial. Alih-alih menjadi ruang bagi gagasan dan terobosan, desa-desa Moronene menjadi tempat bertahan hidup bukan tempat bertumbuh dan berkembang.
Status quo cenderung dijaga terlalu ketat. Minim figur disrupsi yang mendorong perubahan progresif. Eksperimen sosial nyaris tak terlihat; ruang belajar, laboratorium gagasan, atau reinterpretasi adat yang tetap menghormati akar tradisi belum banyak digerakkan oleh generasi muda.
Konflik Internal dan Ketidaksatuan : Menjadi Penghambat Kemajuan.
Pembentukan Kabupaten Bombana pada tahun 2003 seharusnya menjadi momentum emas bagi masyarakat Moronene untuk memperbaiki nasib dan mengejar ketertinggalan. Saat itu, pejabat Bupati pertama memang berasal dari putra daerah Moronene. Namun, dalam pemilihan Bupati definitif berikutnya, masyarakat Moronene gagal mengonsolidasikan suara dan tidak mampu mengantarkan kandidat dari sukunya sendiri ke posisi tertinggi. Salah satu akar masalahnya adalah perpecahan internal dan egosentrisme elite lokal yang sulit dipersatukan dalam satu barisan.
Dua dekade berlalu, dan posisi tertinggi yang berhasil diraih putra Moronene hanyalah kursi Wakil Bupati itu pun di tanah kelahirannya sendiri. Kandidat-kandidat terbaik seringkali terganjal oleh anggapan bahwa mereka tak cukup “kuat” secara finansial untuk bertarung di arena politik lokal yang keras.
Kini, tantangan yang lebih serius datang dari dalam: konflik internal di tubuh adat sendiri. Dualisme kepemimpinan, pertikaian antar elite lokal, dan polarisasi loyalitas telah membuat masyarakat kehilangan arah. Energi sosial yang seharusnya diarahkan untuk membangun, justru habis dalam konflik tentang siapa yang paling berhak atas legitimasi adat.
Dalam kacamata sosiologi, masyarakat yang terfragmentasi akan kesulitan membentuk visi kolektif. Mereka menjadi lebih mudah dipecah, dan semakin sulit dibangun. Tanpa kohesi sosial, gerakan bersama menuju kemajuan hanya akan menjadi mimpi yang terus tertunda.
“Masyarakat yang sibuk saling menyalahkan tak akan sempat membayangkan masa depan bersama.”
Lebih jauh, mentalitas pasrah, sikap menunggu bantuan, dan ketergantungan struktural telah menjebak sebagian masyarakat Moronene dalam apa yang disebut sebagai mentalitas orang miskin yakni cara pandang yang terus-menerus merasa kekurangan, alih-alih melihat dan mengolah potensi yang dimiliki.
Haruskah Kita Menyerah pada Takdir?
Tidak. Justru saat inilah waktu terbaik untuk bertanya: bagaimana seharusnya kita menulis ulang kisah kita?
Kita perlu menghidupkan kembali semangat “memiliki” dan “menghidupi” budaya. Membangun literasi identitas, menggali ulang sejarah lokal, mendorong anak muda masuk ke politik dan pendidikan tinggi bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai delegasi peradaban Moronene. Kita butuh penggerak sunyi, bukan hanya penggugat nyaring.
Kita butuh pemimpin adat yang bukan sekadar pelindung simbol, tetapi juga inovator nilai. Kita butuh elite lokal yang tidak hanya sibuk mengisi jabatan, tapi menata ulang sistem nilai untuk generasi digital. Dan lebih dari itu, kita butuh masyarakat yang mau berhenti menyalahkan masa lalu, dan mulai membayangkan masa depan bersama.
Namun, di tengah kisah keterisolasian dan peluang sejarah yang terlewat, harapan tetap tumbuh. Sejumlah diaspora Moronene yang kini menetap di kota-kota besar bahkan mancanegara telah membuktikan: keterbatasan tidak harus diwariskan. Mereka hadir sebagai dosen, birokrat, aparat, profesional, dan pengusaha. Mereka adalah bukti bahwa akar Moronene pun bisa menjulang di tanah baru—asal ada kemauan untuk bertumbuh, dan keberanian untuk melangkah.
Penutup : Dari Kesadaran Menuju Kebangkitan.
Jika Moronene tertinggal, mungkin bukan karena nasib. Mungkin karena kita belum cukup serius memperjuangkan masa depan. Tapi selama kita punya ingatan, warisan, dan kehendak kolektif, masa depan belum tertutup.
Kita bisa membangun ruang belajar Moronene masa depan. Dimana anak-anak belajar dua bahasa bahasa dunia dan bahasa leluhur. Dimana rumah adat bukan lagi benda mati atau tempat menggelar perkara sengketa saja tapi ruang inovasi. Dimana festival budaya bukan nostalgia, tapi ajang pertukaran global.
“Kita tidak ditakdirkan untuk tertinggal. Kita hanya perlu bangun, belajar, dan bergerak.”
Oleh : Kasra Munara